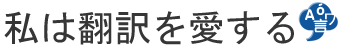- テキスト
- 歴史
Setelah tiga tulisan yang lebih mer
Setelah tiga tulisan yang lebih merupakan—meminjam ungkapan Yasir—
“pertunjukkan gagasan filsafat”, tulisan Neng Dara Affiah menutup buku ini dengan
mengupas pemikiran Ziba Mir-Hosseini dan mencoba menarik relevansinya
untuk hukum keluarga muslim di Indonesia. Tanpa mengabaikan kontribusi ketiga
tulisan lain, tulisan keempat inilah yang paling penting untuk realitas sosial di
Indonesia. Anda boleh saja bicara soal postmetafisika dan dekonstruksi gender,
tetapi semua perbincangan canggih itu kosong saja, bila tidak mendarat ke
realitas hukum. Ada jurang yang dalam di antara pemikiran filosofis Barat yang
sekarang memasuki tahap postmetafisis dan pemikiran hukum Islam. Arendt,
Benhabib dan Butler telah melampaui tidak hanya teosentrisme, melainkan juga
antroposentrisme dengan masuk ke dalam logosentrisme, sementara pemikiran
hukum Islam masih berkutat dengan teosentrisme yang di Barat sudah lama
sekali ditinggalkan. Namun hal itu bukan masalah khas Islam, karena modernitas
memang bertegangan dengan norma-norma agama pada umumnya. Hal itu
menjadi masalah karena kebanyakan masyarakat muslim belum tersekularisasi
seperti Barat, sehingga hukum sakral masih dipercaya sebagai norma politis.
Meringkas sejarah hukum Islam, Affiah, mengacu pada Mir-Hosseini, berpendapat
bahwa akar persoalan stagnasi perkembangan hukum Islam ada di abad ke-
10. Empat mazhab hukum—Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali—“dianggap
telah sempurna, maka pada abad ke-10 terdapat deklarasi bahwa ijtihad telah
tertutup”. Apa yang dilakukan oleh Mir-Hosseini adalah—jika kita boleh memakai
istilah R. Bultmann—semacam “demitologisasi” tradisi Islam. Demitologisasi
adalah bagian wawasan dunia Pencerahan yang mencoba mengasalkan narasinarasi mitis dan sakral pada penyebab-penyebab empiris dan profan. Dengan
ungkapan lain, Mir-Hosseini hendak membuka kembali pintu tafsir rasional
atas hukum sakral dengan memahami konteks historis asal-usul hukum itu.
“pertunjukkan gagasan filsafat”, tulisan Neng Dara Affiah menutup buku ini dengan
mengupas pemikiran Ziba Mir-Hosseini dan mencoba menarik relevansinya
untuk hukum keluarga muslim di Indonesia. Tanpa mengabaikan kontribusi ketiga
tulisan lain, tulisan keempat inilah yang paling penting untuk realitas sosial di
Indonesia. Anda boleh saja bicara soal postmetafisika dan dekonstruksi gender,
tetapi semua perbincangan canggih itu kosong saja, bila tidak mendarat ke
realitas hukum. Ada jurang yang dalam di antara pemikiran filosofis Barat yang
sekarang memasuki tahap postmetafisis dan pemikiran hukum Islam. Arendt,
Benhabib dan Butler telah melampaui tidak hanya teosentrisme, melainkan juga
antroposentrisme dengan masuk ke dalam logosentrisme, sementara pemikiran
hukum Islam masih berkutat dengan teosentrisme yang di Barat sudah lama
sekali ditinggalkan. Namun hal itu bukan masalah khas Islam, karena modernitas
memang bertegangan dengan norma-norma agama pada umumnya. Hal itu
menjadi masalah karena kebanyakan masyarakat muslim belum tersekularisasi
seperti Barat, sehingga hukum sakral masih dipercaya sebagai norma politis.
Meringkas sejarah hukum Islam, Affiah, mengacu pada Mir-Hosseini, berpendapat
bahwa akar persoalan stagnasi perkembangan hukum Islam ada di abad ke-
10. Empat mazhab hukum—Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali—“dianggap
telah sempurna, maka pada abad ke-10 terdapat deklarasi bahwa ijtihad telah
tertutup”. Apa yang dilakukan oleh Mir-Hosseini adalah—jika kita boleh memakai
istilah R. Bultmann—semacam “demitologisasi” tradisi Islam. Demitologisasi
adalah bagian wawasan dunia Pencerahan yang mencoba mengasalkan narasinarasi mitis dan sakral pada penyebab-penyebab empiris dan profan. Dengan
ungkapan lain, Mir-Hosseini hendak membuka kembali pintu tafsir rasional
atas hukum sakral dengan memahami konteks historis asal-usul hukum itu.
0/5000
3文学借入後のフレーズヤーセル-
はNENG処女affiahが
ジバのmiR-ホセイニが考え剥離やインドネシアのイスラム教徒の家族法に
関連性を描くしようとこの本を閉じたことで、 "哲学の考え方を示しています"。他の記事の寄与を無視せずに
第三、第四の記事
インドネシアの社会的現実に最も重要である。あなたはpostmetafisikaや性別解体、
の話をすることができるが法的現実
に上陸していない場合は、すべての話は、洗練された空だった。
今ステージpostmetafisisとイスラム法的思考に入っていると西洋の哲学的思考の間に深い亀裂があります。アーレント、Benhabibと執事が
theocentrismだけを突破したが、またしている
イスラム法を考えながら、ロゴス中心主義を締結する人間中心主義は、まだその西部theocentrismに長い
一度放棄さで苦労されています。しかし、それはイスラムの典型問題ではありません、なぜなら現代
確かに、一般的に宗教的な規範に電圧。
それはイスラム教徒のコミュニティのほとんどが
西部のように世俗化されていないため、問題となった、従ってそれはまだ政治的規範聖法であると考えられている。
のmiR-ホセイニを参考に、イスラム法、affiahの歴史を要約し、主張している問題の根本
イスラム法の開発
10世紀の停滞。法律ハナフィー、マリキ、Shafi'iのとの4校ハンバリーは、 "イジュティハードが閉じられたこと
宣言が、その後10世紀に、完璧と考えられてきた
"。のmiR-ホセイニによって行われるものである場合、我々は言葉を使用するかもしれません
R。ブルトマン-"demythologizing"イスラムの伝統のようなもの。
をdemythologizingする悟りの世界観narasinarasiの一部であり、実証的な原因と俗に神話と神聖帰してみてください。
別の式、のmiR-ホセイニとの合理的な解釈のバックドアを開くについて
法の起源の歴史的文脈を理解することによって神聖な法則。
はNENG処女affiahが
ジバのmiR-ホセイニが考え剥離やインドネシアのイスラム教徒の家族法に
関連性を描くしようとこの本を閉じたことで、 "哲学の考え方を示しています"。他の記事の寄与を無視せずに
第三、第四の記事
インドネシアの社会的現実に最も重要である。あなたはpostmetafisikaや性別解体、
の話をすることができるが法的現実
に上陸していない場合は、すべての話は、洗練された空だった。
今ステージpostmetafisisとイスラム法的思考に入っていると西洋の哲学的思考の間に深い亀裂があります。アーレント、Benhabibと執事が
theocentrismだけを突破したが、またしている
イスラム法を考えながら、ロゴス中心主義を締結する人間中心主義は、まだその西部theocentrismに長い
一度放棄さで苦労されています。しかし、それはイスラムの典型問題ではありません、なぜなら現代
確かに、一般的に宗教的な規範に電圧。
それはイスラム教徒のコミュニティのほとんどが
西部のように世俗化されていないため、問題となった、従ってそれはまだ政治的規範聖法であると考えられている。
のmiR-ホセイニを参考に、イスラム法、affiahの歴史を要約し、主張している問題の根本
イスラム法の開発
10世紀の停滞。法律ハナフィー、マリキ、Shafi'iのとの4校ハンバリーは、 "イジュティハードが閉じられたこと
宣言が、その後10世紀に、完璧と考えられてきた
"。のmiR-ホセイニによって行われるものである場合、我々は言葉を使用するかもしれません
R。ブルトマン-"demythologizing"イスラムの伝統のようなもの。
をdemythologizingする悟りの世界観narasinarasiの一部であり、実証的な原因と俗に神話と神聖帰してみてください。
別の式、のmiR-ホセイニとの合理的な解釈のバックドアを開くについて
法の起源の歴史的文脈を理解することによって神聖な法則。
翻訳されて、しばらくお待ちください..
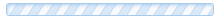
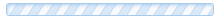
3 つのより多くの書き込みが-言葉を借りると-ヤシール
執筆 Neng Dara Affiah「哲学の考え方を示して」と本を閉じて、
剥離 Ziba ミール ホセイニの思想し、の関連性を描画しようとすると、
インドネシアのイスラム教徒の家族法。3 番目の貢献を無視せず
他の執筆、執筆で第 4 最も重要な社会的な現実をここでは
インドネシア。性別および脱 postmetafisika の話すことができる
がすべてそこに上陸したときに空であるディスカッションを高度な
法の現実。西部の哲学の思考の間にギャップがある
今 postmetafisis およびイスラム教の法的思考の段階に入った。アーレント,
ベンハビブと執事だけではなく teosentrisme を超えているだけでなく
刺激中の logosentrisme に入ると antroposentrisme
イスラム法は、teosentrisme に苦しんでいるまだ西で長いのですべて捨てている
。しかしそれはイスラム教に特有の問題ので現代
確かに電圧 - 一般に宗教的な規範。問題になったので最も
イスラム社会が tersekularisasi
西のようなだから神聖な法律まだ政治の典型と考えられています。
要約されたイスラム法、Affiah、ミール ホセイニを指すの歴史の主張は、根本的な問題
19 世紀のイスラム教の法律のある開発を停滞
10。法律の 4 つの学校-ハナーフィ、マリキ、ハンバリー Shafi —"、それは完璧なと見なされます
宣言そのイジュティ ハードは 10 世紀には閉じられました"
"。どうミール ホセイニによって行われている-私たちを着用することができる場合
r. ブルトマン用語-イスラム教の伝統の"demitologisasi"のようなもの。Demitologisasi
実証および不敬の原因から発信される神聖な神話の narasinarasi にしようとするロマン主義世界の洞察力です。別の式と
の合理的解釈にドアを再開する約ミール ホセイニ
法律の歴史的なコンテキストの把握によって神聖な法律。
執筆 Neng Dara Affiah「哲学の考え方を示して」と本を閉じて、
剥離 Ziba ミール ホセイニの思想し、の関連性を描画しようとすると、
インドネシアのイスラム教徒の家族法。3 番目の貢献を無視せず
他の執筆、執筆で第 4 最も重要な社会的な現実をここでは
インドネシア。性別および脱 postmetafisika の話すことができる
がすべてそこに上陸したときに空であるディスカッションを高度な
法の現実。西部の哲学の思考の間にギャップがある
今 postmetafisis およびイスラム教の法的思考の段階に入った。アーレント,
ベンハビブと執事だけではなく teosentrisme を超えているだけでなく
刺激中の logosentrisme に入ると antroposentrisme
イスラム法は、teosentrisme に苦しんでいるまだ西で長いのですべて捨てている
。しかしそれはイスラム教に特有の問題ので現代
確かに電圧 - 一般に宗教的な規範。問題になったので最も
イスラム社会が tersekularisasi
西のようなだから神聖な法律まだ政治の典型と考えられています。
要約されたイスラム法、Affiah、ミール ホセイニを指すの歴史の主張は、根本的な問題
19 世紀のイスラム教の法律のある開発を停滞
10。法律の 4 つの学校-ハナーフィ、マリキ、ハンバリー Shafi —"、それは完璧なと見なされます
宣言そのイジュティ ハードは 10 世紀には閉じられました"
"。どうミール ホセイニによって行われている-私たちを着用することができる場合
r. ブルトマン用語-イスラム教の伝統の"demitologisasi"のようなもの。Demitologisasi
実証および不敬の原因から発信される神聖な神話の narasinarasi にしようとするロマン主義世界の洞察力です。別の式と
の合理的解釈にドアを再開する約ミール ホセイニ
法律の歴史的なコンテキストの把握によって神聖な法律。
翻訳されて、しばらくお待ちください..
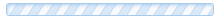
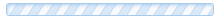
他の言語
翻訳ツールのサポート: アイスランド語, アイルランド語, アゼルバイジャン語, アフリカーンス語, アムハラ語, アラビア語, アルバニア語, アルメニア語, イタリア語, イディッシュ語, イボ語, インドネシア語, ウイグル語, ウェールズ語, ウクライナ語, ウズベク語, ウルドゥ語, エストニア語, エスペラント語, オランダ語, オリヤ語, カザフ語, カタルーニャ語, カンナダ語, ガリシア語, キニヤルワンダ語, キルギス語, ギリシャ語, クメール語, クリンゴン, クルド語, クロアチア語, グジャラト語, コルシカ語, コーサ語, サモア語, ショナ語, シンド語, シンハラ語, ジャワ語, ジョージア(グルジア)語, スウェーデン語, スコットランド ゲール語, スペイン語, スロバキア語, スロベニア語, スワヒリ語, スンダ語, ズールー語, セブアノ語, セルビア語, ソト語, ソマリ語, タイ語, タガログ語, タジク語, タタール語, タミル語, チェコ語, チェワ語, テルグ語, デンマーク語, トルクメン語, トルコ語, ドイツ語, ネパール語, ノルウェー語, ハイチ語, ハウサ語, ハワイ語, ハンガリー語, バスク語, パシュト語, パンジャブ語, ヒンディー語, フィンランド語, フランス語, フリジア語, ブルガリア語, ヘブライ語, ベトナム語, ベラルーシ語, ベンガル語, ペルシャ語, ボスニア語, ポルトガル語, ポーランド語, マオリ語, マケドニア語, マラガシ語, マラヤーラム語, マラーティー語, マルタ語, マレー語, ミャンマー語, モンゴル語, モン語, ヨルバ語, ラオ語, ラテン語, ラトビア語, リトアニア語, ルクセンブルク語, ルーマニア語, ロシア語, 中国語, 日本語, 繁体字中国語, 英語, 言語を検出する, 韓国語, 言語翻訳.
- 偽物のパスポートを使った。
- この事業は、雇用保険に加入する資格のない短期就労者や長期失業者に職業訓練の機会を
- pige
- 花束
- CYCLING star Peter Sagan looks to be com
- 独立記念日
- dreng
- 自由な家族
- 花
- 自由時間
- 花束
- Centraal gelegen in het oude centrum van
- dorgi
- In dit kleinschalige nieuwbouwproject mi
- 花束
- 失業者の職業訓練を支援する国の事業で支援金などをだまし取ったとして、福岡県警が、
- 花束
- Een buitenkansje!Leuk 2-kamer appartemen
- ink
- Engelandlaan 340, Haarlem€ 550 /mndDit r
- 花束
- 永遠の愛
- Oh! Haluaisin syödä
- 花束